Menyelami Fitrah Kemanusiaan Kita
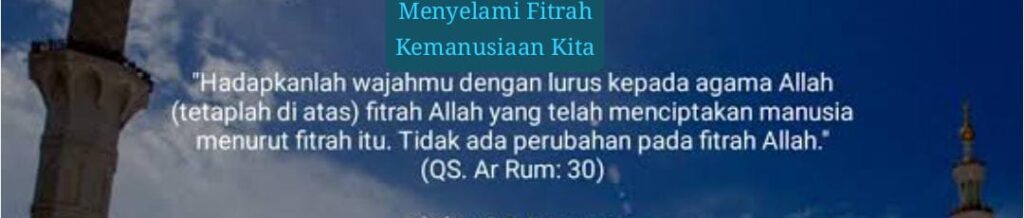
Oleh: Bambang Irawan
Setiap kali Idul Fitri tiba, gegap gempita sukacita menyelimuti negeri. Ucapan “Selamat Hari Raya” dan “Minal Aidin wal-Faizin” bergema di mana-mana. Tapi, di balik kemeriahan itu, ada pertanyaan mendasar yang kerap terabaikan: Benarkah kita telah meraih kemenangan?
Kemenangan sejati dalam Idul Fitri bukanlah sekadar usainya bulan puasa atau berhasil menahan lapar dan dahaga. Rasulullah mengingatkan, “Banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga.” (HR. Ibnu Majah). Kemenangan sejati terletak pada kemampuan kita mengalahkan hawa nafsu—musuh yang licik, karena ia datang bukan dengan wajah menakutkan, tetapi justru dalam bentuk kesenangan sesaat yang menggiurkan.
Puasa dan Ujian Kejujuran Diri
Ramadhan adalah bulan pelatihan intensif untuk mengendalikan diri. Namun, ujian sesungguhnya justru datang setelahnya: Apakah kita tetap konsisten? Di hari raya, kita bersalaman dan saling memaafkan, tetapi apakah sifat riya’, dengki, atau kesombongan benar-benar hilang dari hati? Atau justru kita terjebak dalam euforia yang dangkal—sibuk memamerkan baju baru, mengunggah foto hidangan lebaran, sementara kepedulian kepada tetangga yang kelaparan tetap minim?
Syawal adalah cermin. Di sinilah kita mengevaluasi: Apakah ibadah Ramadhan meninggalkan bekas pada karakter kita? Jika selama puasa kita mudah tersulut emosi, atau setelahnya kembali kepada kebiasaan buruk, maka mungkin “kemenangan” itu masih ilusif.
Zakat Fitrah Mengingatkan Kembali Fitrah Sosial Kita
Islam tidak hanya mengajarkan kesalehan individual, tetapi juga kesalehan sosial. Zakat fitrah—yang akar katanya (fithri) berarti “suci” atau “asal penciptaan”—adalah pengingat bahwa kepedulian kepada sesama adalah bagian dari jati diri manusia. Sayangnya, fitrah ini sering terkubur oleh individualisme dan nafsu serakah.
Kita hidup di era di orang lebih bangga membeli barang mewah ketimbang menyantuni anak yatim, lebih getol memamerkan kekayaan daripada menengok saudara yang terlilit utang. Padahal, Nabi bersabda, “Orang yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, bukanlah bagian dari mereka.” (HR. Al-Hakim).
Agama yang Fitrah: Jalan Pulang ke Jati Diri
Allah berfirman, “Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan lurus; (sesuai) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.” (QS. Ar-Rum: 30). Agama bukanlah aturan kaku yang dipaksakan, melainkan panduan yang selaras dengan naluri manusia untuk berbuat baik, menyayangi, dan merindukan kebenaran.
Jika ada ajaran agama yang terasa “berat”, seringkali itu bukan karena bertentangan dengan fitrah, melainkan karena nafsu kitalah yang telah terkotori. Contoh sederhana: berderma itu fitrah—setiap orang bahagia ketika memberi. Tapi nafsu serakahlah yang membisikkan, “Jangan, nanti kamu miskin!”
Idul Fitri yang Bermakna: Kembali ke Fitrah
Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum:
- Evaluasi diri: Apakah kita lebih sabar, dermawan, dan tulus dibanding sebelum Ramadhan?
- Memperbaiki hubungan: Tak cukup sekadar “mohon maaf lahir batin”, tetapi juga membuka diri untuk lebih peka terhadap kesusahan orang lain.
- Menjaga konsistensi: Ibadah bukan ritual musiman, melainkan komitmen sepanjang hayat.
Idul Fitri sejati adalah ketika kita kembali ke fitrah sebagai manusia: hamba yang tunduk kepada Tuhan, makhluk sosial yang peduli, dan khalifah yang menjaga harmoni alam. Semoga kita tidak hanya merayakan kemenangan semu, tetapi benar-benar menjadi pribadi yang fitri—kembali suci.
Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali fitrah.




