Jejak Panjang Ketimpangan Pangan
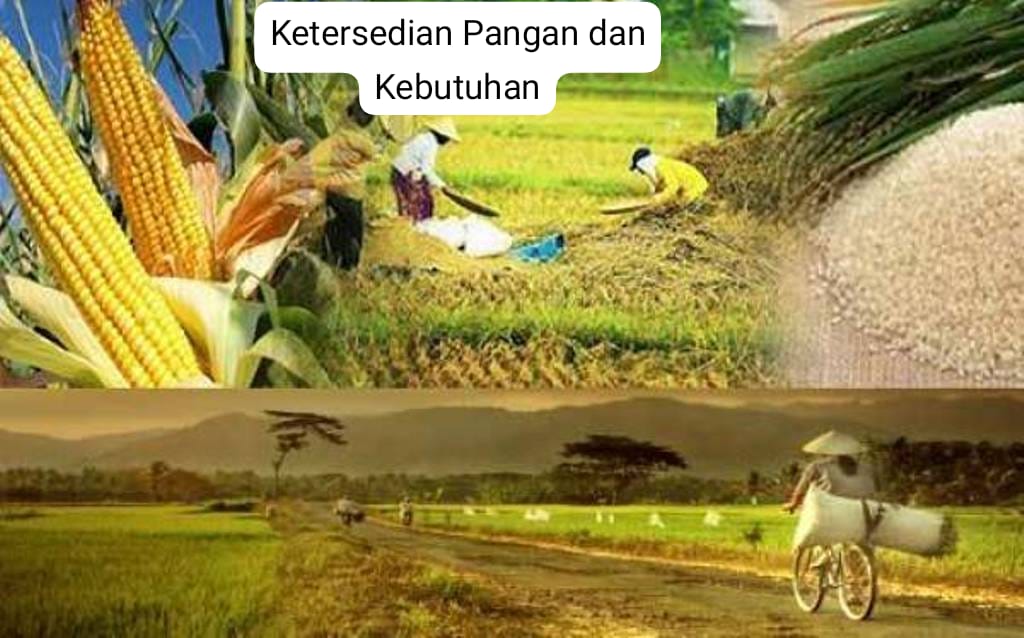
Oleh: Bambang Irawan
Sekitar 320 juta tahun lalu, bumi hanya mengenal satu daratan luas: Kemudian, lempeng-lempeng tektonik bergerak, benua terpecah, iklim berubah—dan di situlah cerita ketidakmerataan pangan dimulai. Daerah tropis, dengan limpahan sinar matahari dan air, menjadi pusat evolusi keanekaragaman hayati. Indonesia, yang dianugerahi kedua hal itu, seharusnya menjadi raksasa pangan dunia. Namun, mengapa kita justru bergantung pada impor beras, gandum, bahkan garam?
Dari Fotosintesis hingga Food Estate: Paradoks Negara Agraris
Fotosintesis adalah fondasi peradaban pangan. Di khatulistiwa, di mana matahari tak pernah absen, seharusnya tanaman tumbuh subur sepanjang tahun. Namun, sejarah menunjukkan bahwa ketersediaan alam tidak otomatis menjamin ketahanan pangan.
Nenek moyang kita sudah membuktikannya: mereka berpindah dari berburu ke bercocok tanam ketika menemukan tanah subur. Jawa, Sumatra, dan Sulawesi menjadi pusat pertanian awal karena kesuburannya.
Tapi hari ini, kita menyaksikan ironi: lahan pertanian menyusut 60.000 hektar per tahun (BPS, 2023), beralih menjadi pabrik, perumahan, dan jalan tol. Kita bangga disebut negara agraris, tetapi data Kementerian Pertanian mengungkapkan bahwa 75% kebutuhan kedelai dan 50% gula nasional masih diimpor. Di mana salahnya?
Alih Fungsi Lahan: Bunuh Diri Ketahanan Pangan
Setiap hektar sawah yang berubah menjadi perumahan elite bukan hanya kehilangan produktivitas, tetapi juga memutus rantai ekologi: mata air menghilang, mikroorganisme tanah mati, dan pengetahuan lokal terkikis. Impor pangan adalah konsekuensi logis dari kebijakan yang *mengorbankan lahan pangan untuk pembangunan infrastruktur tanpa strategi substitusi.
Program food estate seharusnya menjadi solusi, tetapi kerap terjebak dalam paradoks: membuka hutan untuk lahan pertanian baru justru merusak ekosistem yang sudah ada. Jika tidak diimbangi dengan proteksi lahan pertanian produktif, upaya ini hanya akan menjadi tempelan tambal sulam.
Kembali ke Akar: Integrasi Kebijakan dari Presiden hingga Desa
Pangan bukan sekadar urusan Kementerian Pertanian. Ia adalah persoalan geopolitik, ekonomi, dan budaya. Butuh superteam kebijakan yang melibatkan:
- Pemerintah pusat dengan regulasi tegas soal alih fungsi lahan.
- Pemda yang berkomitmen menjadikan lahan pertanian sebagai aset strategis.
- Swasta dengan investasi berbasis keberlanjutan, bukan eksploitasi.
- Masyarakat yang didorong kembali ke pertanian dengan insentif nyata.
Retret para kepala daerah bersama presiden belakangan ini adalah sinyal baik, tetapi harus diterjemahkan dalam peta jalan konkret, bukan sekadar seremonial.
Masa Depan Pangan: Antara Teknologi dan Kearifan Lokal
Kita tidak bisa hanya mengandalkan revolusi hijau 2.0 dengan pupuk kimia dan benih hibrida. Perlu kolaborasi teknologi dan kearifan lokal:
- Pertanian presisi dengan IoT dan drone untuk efisiensi.
- Revitalisasi pangan lokal seperti sagu, sorgum, dan umbi-umbian.
- Edukasi generasi muda bahwa bertani bukan profesi kuno, melainkan senjata strategis di era krisis iklim.
Pangan adalah Jejak Peradaban
Sejarah pangan adalah cermin peradaban. Jika kita terus mengimpor, kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri. Jika kita serius dengan kedaulatan pangan, maka lindungi dan benahi lahan sesuai kepemilikan, hargai petani, dan kelola pangan dengan visi lintas generasi.
Indonesia harus memilih: menjadi pasar pangan dunia, atau tuan rumah di negeri sendiri.




